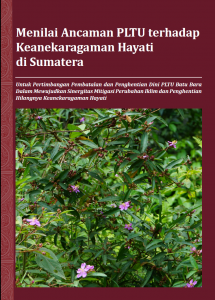Siaran Pers
Jatam Sulawesi Tengah & Perkumpulan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER)
Jakarta, 11 Mei 2022
Saat ini dunia sedang mengembangkan moda transportasi kendaraan listrik sebagai upaya dalam menangani krisis iklim. Nikel telah menjadi komoditas yang semakin diminati karena produksi baterai untuk kendaraan listrik mulai meningkat. Semakin banyak perusahaan mobil yang berlomba untuk mengembangkan teknologi baterai yang berbeda sesuai dengan kebutuhan kinerja terbaik.

Tesla dan Pemerintah Indonesia sedang berencana menciptakan kerjasama investasi nikel batere. Organisasi lingkungan di Indonesia, yakni Jatam Sulawesi Tengah dan Perkumpulan AEER menyorot perlunya kebijakan agar nikel dari Indonesia tidak menciptakan persoalan lingkungan baru sehingga bertentangan dengan tujuan pengembangan transportasi rendah karbon. Tesla dan Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan dampak buruk terhadap lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas pertambangan nikel. Pemenuhan kebutuhan baterai berbasis nikel harus mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Jatam Sulawesi Tengah dan AEER pun mengirim surat kepada CEO Tesla, Elon Musk pada 11 Mei 2022. Dalam suratnya, mereka mengingatkan agar Elon Musk tetap memegang komitmen yang disampaikan dalam rapat pemegang saham tahunan Tesla September 2020, bahwa dia menawarkan kontrak jangka panjang bagi perusahaan yang dapat menambang nikel dengan satu syarat, yaitu tidak mencemari lingkungan.
Pius Ginting, Koordinator Perkumpulan AEER menyatakan poin yang disampaikan dalam surat bahwa apabila Tesla ingin berinvestasi di Indonesia, agar sumber energi untuk aktivitas produksi nikel tidak berasal dari PLTU batubara, karena akan bertentangan dengan salah satu tujuan untuk membeli kendaraan listrik yaitu mengurangi total emisi gas rumah kaca.
Moh Taufik, Kordinator Jatam Sulawesi Tengah menambahkan, penggunaan nikel asal Indonesia oleh Tesla agar tidak menerapkan metode Deep-Sea Tailings Placement (DSTP) untuk pembuangan limbah. Tailing dalam volume besar dengan potensi racunnya menjadi salah satu isu lingkungan penting dalam dunia pertambangan.
Menurut United States Environmental Protection Agency (EPA), kontaminasi air akibat pertambangan termasuk tiga ancaman lingkungan terbesar di dunia. Tiga lokasi yang menjadi rencana DSTP adalah Morowali, Obi, dan Weda. Ketiga lokasi tersebut terletak pada kawasan coral triangle. Kawasan ini mengandung keragaman spesies terumbu karang yang sangat tinggi. Apabila limbah pertambangan dibuang ke laut, akan menyebabkan pemutihan karang massal dan dapat menyebabkan penurunan biodiversitas.
Menurut kajian yang dilakukan oleh Perkumpulan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara untuk pengolahan nikel di Indonesia telah meningkatkan polusi udara dan masalah kesehatan bagi masyarakat lokal di Bahodopi, Morowali. Debu batu bara mendatangi rumah para warga, mengakibatkan banyak orang mengidap Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).